Era Nuklir Ketiga di Asia Tenggara [Translation]
Komentar ini awalnya ditulis dalam bahasa Inggris. Artikel di bawah ini telah diterjemahkan dengan menggunakan alat penerjemah. Klik di sini untuk melihat versi asli bahasa Inggris dari artikel ini.
Senjata nuklir telah kembali ke panggung utama politik global. Modernisasi dan dalam beberapa kasus perluasan persediaan nuklir, perubahan teknologi yang cepat dalam teknologi senjata dan sistem pendukungnya, melonggarnya pengekangan retorika dan militer, krisis yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir, kembalinya persaingan nuklir berkekuatan besar, serta erosi dan rusaknya kerangka kerja normatif dan hukum internasional, semuanya menunjukkan dunia nuklir yang semakin berbahaya, tidak dapat diprediksi, dan berbeda. Pada saat yang sama, mayoritas negara anggota PBB telah menolak kembalinya politik senjata nuklir ini dengan mengklaim memiliki peran dalam membentuk tatanan normatif nuklir, dan secara langsung menentang kepemilikan senjata nuklir yang terus berlanjut sebagai alat penangkal. Pada saat yang sama, ada minat yang meningkat di seluruh negara berkembang untuk mengakses manfaat teknologi nuklir yang memungkinkan untuk menyediakan energi bebas karbon bagi ekonomi mereka yang berkembang pesat. Secara keseluruhan, dinamika dan pandangan dunia nuklir yang terkadang antagonis ini semakin dipandang sebagai mewakili era baru dalam sejarah nuklir kita, dan mungkin merupakan awal dari “Zaman Nuklir Ketiga.“[1]
Meskipun politik nuklir global mungkin menjadi lebih terpecah, apa yang sering mendominasi perdebatan ilmiah dan profesional mengenai tantangan terhadap tatanan nuklir global adalah etnosentrisme nuklir Barat – yaitu, ketidakmampuan untuk memahami dunia nuklir kita di luar perspektif yang dipegang oleh para elit di Barat, dan pada tingkat yang lebih rendah, segelintir negara yang mengoperasikan senjata nuklir. Hal ini sering kali juga berfungsi untuk mengukuhkan gagasan senjata nuklir sebagai artefak permanen politik internasional. Apa yang sering hilang dari gambaran ini adalah pengalaman, sudut pandang, dan keinginan negara-negara dan orang-orang di belahan dunia lain yang tidak mengambil bagian dalam penangkalan nuklir, tetapi tetap akan terpengaruh – baik secara positif maupun negatif – oleh teknologi nuklir. Melihat tatanan nuklir global melalui narasi keamanan yang dominan tidak hanya mengesampingkan perspektif yang sama validnya dari negara-negara lain, tetapi yang lebih penting adalah merusak kemampuan kita untuk benar-benar memahami universalitas risiko nuklir.
Pada bulan Maret 2024, proyek Zaman Nuklir Ketiga menyelenggarakan lokakarya di Jakarta untuk mengumpulkan para ahli dari seluruh Asia Tenggara guna mengupas dan mengeksplorasi apa arti konteks nuklir yang sedang berkembang ini bagi kawasan yang secara historis tidak tercemar oleh bahaya nuklir. Melihat dunia nuklir kita melalui lensa non-Barat, non-bersenjata nuklir mengungkapkan gambaran yang sangat berbeda tentang tatanan nuklir global: bukan hanya penolakan budaya yang kuat terhadap senjata nuklir sebagai alat penangkal dan bahaya, tetapi pada saat yang sama keyakinan bahwa teknologi nuklir dapat berperan dalam masa depan yang damai dan adil.
Mempertahankan sentralitas ASEAN
Terlepas dari kekhawatiran tentang jaringan penyelundupan nuklir, Asia Tenggara telah menjadi wilayah yang cukup tidak tersentuh oleh ancaman nuklir. Tetapi dengan meningkatnya persepsi konfrontasi antara Cina dan Amerika Serikat (serta sekutu regional Amerika Serikat), dan kesadaran bahwa Asia Tenggara kemungkinan akan menjadi medan operasi utama dalam konflik apa pun di antara negara-negara tersebut, risiko nuklir menjadi jauh lebih nyata. Perjanjian Bangkok tahun 1995 menetapkan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), yang melarang sepuluh anggotanya[2] untuk mengembangkan, membuat, mengakuisisi, atau memiliki senjata nuklir. Meskipun ada harapan bahwa negara-negara bersenjata nuklir akan menghormati SEANWFZ, kenyataannya adalah bahwa kapal-kapal militer bersenjata nuklir dan kapal-kapal militer berpeluru kendali nuklir mungkin telah transit di wilayah ini, dan Laut Cina Selatan kemungkinan akan menjadi medan pertempuran utama dalam perang di masa depan.
Menariknya, tidak ada bukti bahwa kekhawatiran akan bentrokan antara negara-negara besar, atau risiko terlibat dalam konfrontasi dengan negara bersenjata nuklir besar, secara langsung mendorong program modernisasi militer di Asia Tenggara. Sejumlah negara di kawasan ini mengubah postur pertahanan mereka atau mengejar pembangunan militer yang berarti, terutama investasi kapal selam, tetapi hal ini tampaknya didorong oleh dinamika internal dan kebutuhan untuk melindungi domain maritim yang penting secara strategis, termasuk Selat Malaka dan Zona Ekonomi Eksklusif. Sebagian besar ahli sepakat bahwa hal ini sangat berbeda dengan tekanan dan tujuan yang mendorong modernisasi militer di – misalnya – Eropa.
Memang, dalam banyak hal, membandingkan situasi keamanan di Asia Tenggara dan peran ASEAN dengan peran NATO di Euro-Atlantik tidaklah membantu. Sementara perdebatan saat ini di NATO berfokus pada bagaimana memperluas kemampuan konvensional gabungan dan memperkuat kredibilitas payung nuklir, modernisasi militer di Asia Tenggara terutama didorong oleh masing-masing negara dan tidak dikoordinasikan melalui mekanisme regional ASEAN. ASEAN tidak beroperasi dengan logika yang sama dengan NATO atau klausul pertahanan kolektif “Pasal V”, dan tidak ada perencanaan untuk aksi militer terhadap musuh tertentu. Hubungan ASEAN tidak dicirikan oleh ancaman keamanan yang bersifat hard power, tetapi oleh prioritas bersama untuk kemitraan ekonomi dan pembangunan. Hal ini, misalnya, terlihat jelas dalam Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, di mana negara-negara anggota mengungkapkan keinginan untuk sentralitas ASEAN dan visi terpadu tentang arsitektur regional yang menangani kerja sama dan kemakmuran, bukan persaingan.
Jika isu nuklir muncul dalam politik keamanan Asia Tenggara, maka hal itu adalah kekhawatiran akan penyelundupan nuklir dan kemungkinan aktor non-negara mendapatkan akses ke bahan nuklir melalui sistem pelayaran laut yang sangat besar di kawasan ini, dan kekhawatiran yang semakin besar akan kecelakaan nuklir. Hal ini dapat dikatakan mencerminkan fakta bahwa tantangan “Zaman Nuklir Kedua”, seperti aktor-aktor “nakal”, keamanan nuklir, dan terorisme nuklir yang mendominasi perdebatan di Barat dua dekade yang lalu, masih menjadi inti dari perencanaan keamanan di Asia Tenggara saat ini. Pada saat yang sama, negara-negara Asia Tenggara mendukung gagasan bahwa risiko keamanan nuklir berlaku untuk semua bahan dan fasilitas nuklir – termasuk yang digunakan untuk keperluan militer – sehingga penanganan keamanan nuklir memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencerminkan pergeseran dari narasi yang berpusat pada Barat yang sebagian besar membatasi risiko-risiko ini pada bahan dan fasilitas nuklir untuk tujuan damai. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bahwa pilihan-pilihan yang diambil oleh negara-negara yang mengoperasikan teknologi nuklir semakin berdampak pada Asia Tenggara. Hal ini memetakan perbedaan penting dalam hirarki ancaman nuklir dan budaya strategis antara masyarakat Barat dan Asia Tenggara: masyarakat yang memprioritaskan atau tampaknya menerima ancaman keamanan dan militer, dan masyarakat yang menolak atau setidaknya berusaha untuk meminimalkan pandangan politik internasional semacam itu.
Banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, dan menginginkan hubungan yang lebih damai di antara kedua “kekuatan besar” tersebut. Cina adalah pemain ekonomi utama di kawasan ini dan sumber investasi asing langsung yang signifikan, sementara Amerika Serikat sering dilihat oleh beberapa orang sebagai mitra keamanan yang lebih disukai. Terlepas dari hubungan budaya, India – kekuatan bersenjata nuklir regional utama lainnya, tampaknya memiliki pengaruh yang relatif kecil di Asia Tenggara. Bagi sebagian besar negara ASEAN, tidak ada keinginan untuk “memilih sisi” dalam konflik di masa depan, dan bahkan ada sedikit keinginan untuk terlibat dalam persaingan nuklir kekuatan besar di kawasan ini.
Para pemrotes dan pembela
Meskipun jauh dari homogen, negara-negara Asia Tenggara dapat dikategorikan sebagai “pemrotes” yang mengkritik kurangnya kemajuan dari lima negara pemilik senjata nuklir untuk bekerja “dengan itikad baik” menuju perlucutan senjata, dan menjunjung tinggi komitmen hukum mereka di bawah Traktat Non-proliferasi (NPT) 1968. Dilihat dari sudut pandang ini, NWFZ di Asia Tenggara dipandang sebagai penguatan upaya global menuju perlucutan senjata nuklir dan sangat penting mengingat kedekatan kawasan ini dengan negara-negara bersenjata nuklir seperti Cina, Korea Utara, India, dan Pakistan. Akan tetapi, SEANWFZ merupakan satu-satunya NWFZ regional yang belum ditandatangani oleh AS, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Negara-negara bersenjata nuklir enggan menandatangani Protokol SEANWFZ karena kekhawatiran akan kebebasan navigasi, masalah verifikasi, dan potensi dampak terhadap keampuhan penangkal nuklir dan operasi nuklir mereka.
Secara historis, protes Asia Tenggara untuk perlucutan senjata nuklir didasarkan pada pembelaan tatanan nuklir global terhadap ketidakadilan yang dirasakan dari rezim NPT dari luar. Di bawah rezim NPT, negara-negara non-nuklir telah memenuhi kewajiban non-proliferasi yang ketat sementara negara-negara pemilik senjata nuklir tidak dianggap bertindak “dengan itikad baik” dalam hal kemajuan menuju perlucutan senjata nuklir. Gerakan ini telah berkembang: hari ini, protes mereka melibatkan tantangan langsung terhadap dasar praktik pencegahan nuklir oleh negara-negara besar dan negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Hal ini terutama terlihat dalam dukungan dan antusiasme sebagian besar negara-negara Asia Tenggara di balik Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW).[3]
TPNW secara khusus disambut baik di kawasan ini karena memungkinkan lebih banyak negara bersenjata non-nuklir untuk bertindak sebagai pemangku kepentingan dalam tata kelola nuklir global. TPNW juga populer karena narasi kemanusiaan yang kuat memperluas konsepsi risiko nuklir dari yang terbatas pada perang nuklir dan proliferasi, menjadi konsepsi yang mempermasalahkan kepemilikan senjata nuklir negara mana pun dan konsekuensi bencana dari ledakan nuklir apa pun. Negara-negara pemilik senjata nuklir menolak TPNW terutama karena mereka percaya bahwa keamanan mereka bergantung pada pemeliharaan penangkal nuklir yang efektif dan kredibel. Hal ini menandai pergeseran dalam hubungan di mana, dalam proses menuju larangan nuklir global yang diamanatkan PBB, negara-negara non senjata nuklir mengasumsikan badan normatif sementara negara-negara senjata nuklir mendapat giliran untuk mengasumsikan peran baru sebagai “pemrotes”.
Hal ini menunjukkan bahwa di Era Nuklir Ketiga, gagasan tentang tanggung jawab tidak dapat lagi diterima begitu saja. Logika etnosentrisme nuklir Barat, bersama dengan anggapan bahwa aktor-aktor tertentu “bertanggung jawab”, semakin ditantang. Pandangan yang tersebar luas di kalangan elit kebijakan Asia Tenggara adalah bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir tidak dapat lagi dianggap bertanggung jawab jika mereka terus meningkatkan risiko bencana yang tak terkendali melalui retorika nuklir dan upaya modernisasi daripada memenuhi kewajiban pelucutan senjata nuklir mereka.
Keengganan untuk terlibat dalam persaingan strategis kekuatan besar mungkin sebagian menjelaskan mengapa negara-negara ini memiliki tanggapan yang beragam terhadap kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS. Di seluruh Asia Tenggara, kekhawatiran tentang AUKUS bervariasi mulai dari bagaimana perjanjian itu berdampak pada keseimbangan strategis di Indo-Pasifik yang lebih luas dan kemungkinan konfrontasi antara Amerika Serikat dan Cina, hingga preseden yang ditetapkannya mengingat bahwa Australia tidak akan terikat pada standar non-proliferasi seperti yang diwajibkan oleh Protokol Tambahan IAEA. Dengan cara ini, banyak negara Asia Tenggara juga melihat diri mereka sebagai “pembela” tatanan nuklir.
Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun memperkuat perlucutan senjata nuklir merupakan sentimen yang populer di Asia Tenggara, tidak seperti negara-negara Afrika dan Amerika Latin, negara-negara ASEAN biasanya tidak memiliki posisi yang sama dalam menanggapi perkembangan nuklir dalam forum nuklir multilateral (seperti NPT dan TPNW). Selain itu, tingkat pemahaman tentang masalah senjata nuklir di kawasan ini relatif terbatas dan sebagian besar terjadi di tingkat elit (meskipun sinyal dukungan untuk pelucutan senjata nuklir sering kali berjalan dengan baik di dalam negeri).
Memanfaatkan kekuatan atom
Pada awal era atom, ada keyakinan bahwa teknologi nuklir dapat dikendalikan dan aplikasi energi nuklir sipil yang meluas dapat hidup berdampingan dengan sistem pelucutan senjata nuklir yang terkelola. Tentu saja, beberapa negara maju bergerak maju dan membangun infrastruktur energi nuklir yang signifikan, tetapi hal ini sebagian besar masih terbatas pada dunia Barat yang sudah maju. Baru-baru ini saja pertemuan berbagai faktor telah membuka kemungkinan pengembangan teknologi nuklir di sebagian besar dunia pasca-kolonial. Sejauh pembingkaian langkah menuju Zaman Nuklir Ketiga memiliki daya tarik di Asia Tenggara, maka hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana teknologi nuklir dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi dan memenuhi permintaan energi yang berkembang pesat.
Secara historis, ada persepsi bahwa dominasi narasi non-proliferasi (Barat) telah berdampak langsung pada kemampuan banyak negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan kekuatan teknologi nuklir damai. Akses terhadap teknologi nuklir untuk pengembangan adalah salah satu alasan utama mengapa banyak negara non senjata nuklir setuju untuk bergabung dengan rezim non-proliferasi, dan dapat dikatakan menandatangani TPNW. Tetapi sementara banyak masyarakat Barat yang sudah maju telah mendapatkan keuntungan dari aplikasi non-militer teknologi nuklir untuk pembangkit energi, pembangunan ekonomi dan penelitian ilmiah, kesempatan yang sama sebagian besar tidak diberikan kepada negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Ada keyakinan kuat bahwa kekhawatiran non-proliferasi Barat telah diprioritaskan secara tidak adil di atas aplikasi perkembangan teknologi nuklir yang cukup besar bagi manusia dan masyarakat di belahan dunia lain. Persepsi ketidakadilan ini, dan keyakinan akan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengakses teknologi nuklir untuk tujuan damai, juga sering kali diabaikan dalam kajian-kajian tentang tatanan nuklir global.
Meskipun penggunaan tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik saat ini sedang mengalami kemunduran di beberapa negara maju, beberapa negara di Asia Tenggara telah meningkatkan minat mereka untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (terutama, Indonesia, Filipina dan Vietnam). Meskipun kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang pada tahun 2011 dan kerentanan banyak negara di kawasan ini terhadap gempa bumi telah meredam antusiasme ini, namun kepentingan politik dari Net Zero dan pengurangan emisi karbon tampaknya akan menjadikan nuklir sebagai bagian penting dari masa depan energi di Asia Tenggara. Hal ini menyoroti pentingnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan relevan bagi masyarakat di kawasan ini ketika berusaha memahami Asia Tenggara di Era Nuklir Ketiga: apakah akses ke teknologi nuklir tidak dapat dicabut? Bagaimana teknologi nuklir dapat berkontribusi pada keamanan energi dan mitigasi perubahan iklim? Apa kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB di kawasan ini? Fakta bahwa Cina, Rusia, dan Amerika Serikat terlibat dalam diskusi untuk membangun fasilitas nuklir sipil di kawasan ini membuat hal ini semakin menonjol.
Akses terhadap teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan bagian dari dinamika yang lebih besar di seluruh bagian dari apa yang sering disebut sebagai Global South, di mana ada pandangan bahwa negara-negara maju belum berbagi hasil dari teknologi nuklir secara adil. Sejak awal, Gerakan Non-Blok, sebuah asosiasi politik longgar yang terdiri dari 120 negara yang tidak secara resmi bersekutu dengan atau menentang kekuatan besar mana pun (termasuk semua negara Asia Tenggara), telah mendorong “keadilan redistributif” dan hak-hak semua negara untuk memanfaatkan kekuatan atom. Karena alasan inilah negara-negara non-blok, termasuk sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, mendukung hak Iran untuk memperkaya uranium selama mereka memenuhi kewajiban non-proliferasi, dan menganggap kekhawatiran proliferasi senjata di Barat sebagai sesuatu yang berlebihan. Secara umum, ada keyakinan yang kuat bahwa standar ganda non-proliferasi merusak integritas tatanan nuklir global.
Nuklir berjangka
Mungkin hal yang paling mencolok dari perdebatan nuklir di Asia Tenggara adalah bahwa tidak ada penerimaan yang sama (dengan enggan atau tidak) terhadap kekekalan senjata nuklir dan penangkalan nuklir yang tampaknya ada dalam narasi keamanan ortodoks Barat. Hal ini merupakan cerminan dari pengalaman sejarah tertentu, dan fakta bahwa selain periode yang sangat singkat pada tahun 1960-an, tidak ada negara di Asia Tenggara yang secara serius tertarik untuk membangun senjata nuklir, atau melihat peran pencegahan nuklir. Saat ini, perdebatan nuklir di Asia Tenggara mencerminkan dinamika ganda di kawasan ini: meningkatnya kekhawatiran tentang risiko nuklir universal, yang didorong oleh memburuknya hubungan di antara negara-negara besar dan pengembangan sistem senjata yang mengganggu kestabilan yang merusak komitmen perlucutan senjata dan non-proliferasi, ditambah dengan meningkatnya minat terhadap penggunaan nuklir untuk kepentingan sipil dari teknologi nuklir. Meskipun demikian, tidak ada satu “pandangan” yang sama mengenai makna Era Nuklir Ketiga di Asia Tenggara; politik dalam negeri, aliansi, dan geografi menciptakan agenda yang sangat berbeda.
Masih kurang jelas bagaimana atau apakah negara-negara di Asia Tenggara, atau bahkan di seluruh Dunia Selatan, dapat menghasilkan lembaga atau kekuatan yang cukup untuk mengubah konteks yang sedang berlangsung ini. Juga tidak jelas bagaimana popularitas perlucutan senjata nuklir sebagai isu sosial dan politik di PBB diterjemahkan ke dalam tekanan global untuk perubahan yang sesungguhnya. Mungkin sebagai hasilnya, masih harus dilihat apa dampak TPNW dan tekanan yang lebih terkoordinasi dari negara-negara bersenjata non-nuklir dan sekutu LSM mereka terhadap negara-negara bersenjata nuklir dan sekutu penangkalan mereka yang lebih luas, dan apakah hal ini akan mengesampingkan kekhawatiran keamanan nasional yang dirasakan oleh para elit di negara-negara bersenjata nuklir di masa mendatang.
Namun, mungkin yang membuat Era Nuklir Ketiga berbeda dengan era nuklir sebelumnya adalah kenyataan bahwa kita bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Suara Asia Tenggara dan negara-negara Selatan Global lainnya semakin didengar dan membentuk perdebatan, dan tidak hanya di pinggiran. Wacana nuklir yang lebih luas sedang dalam proses menjadi tantangan jika tidak diubah, dan sudut pandang yang sebelumnya terpinggirkan yang membayangkan masa depan nuklir alternatif semakin membentuk ruang akademis dan kebijakan dalam hal politik nuklir. Pada akhirnya, kekuatan destruktif senjata nuklir (dan kemungkinan utopis energi nuklir) membuat semua orang di planet ini menjadi pemangku kepentingan di Zaman Nuklir Ketiga, dan merupakan hal yang baik bahwa narasi dan visi yang saling bersaing menjadi lebih menonjol dan terlibat.
Catatan Akhir
[1] Dalam wacana Barat, Zaman Nuklir Pertama dikatakan terjadi antara 1945-1990 dan berfokus pada persaingan nuklir negara adidaya di jantung Perang Dingin, dan Zaman Nuklir Kedua dikatakan terjadi pada tahun 1990-an ketika perhatian beralih ke ancaman nuklir dari negara jahat dan teroris.
[2] Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
[3] Dari negara-negara Asia Tenggara, hanya Singapura yang belum menandatangani TPNW.
About the Authors
Andrew Futter is Professor of International Politics at the University of Leicester, UK and leads the European Research Council-funded Third Nuclear Age project.
Felicia Yuwono is an official with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and a Doctoral Researcher at the Department of War Studies, King’s College London.
Pendapat yang disampaikan di atas mewakili pandangan penulis dan tidak mencerminkan posisi Asia-Pacific Leadership Network atau anggotanya.
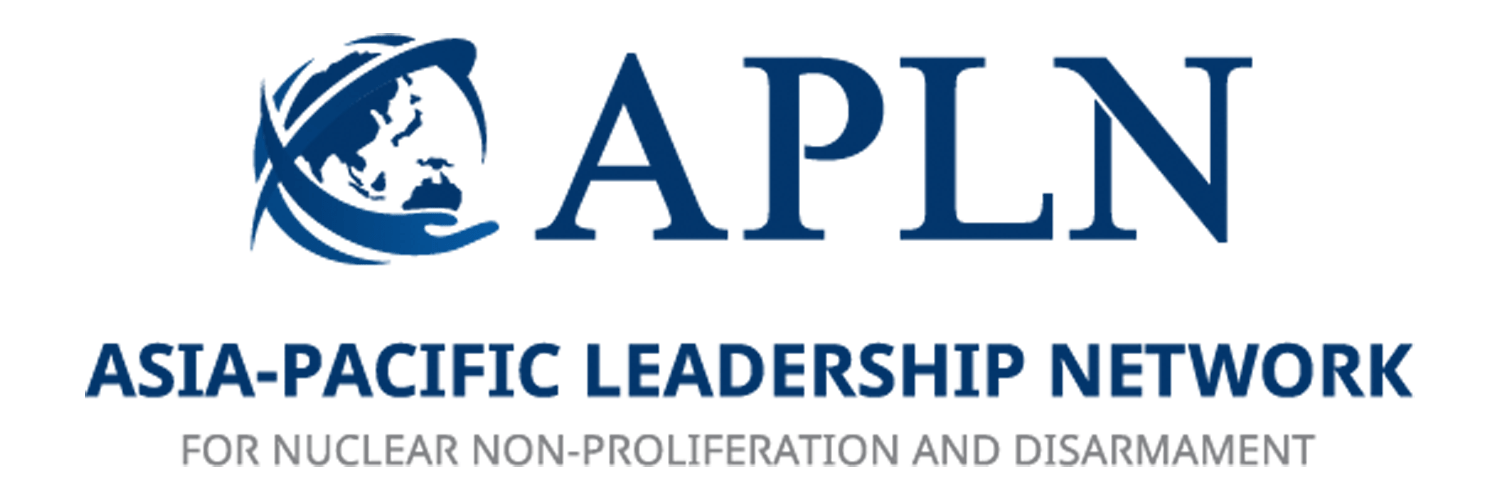
![Era Nuklir Ketiga di Asia Tenggara [Translation]](https://cms.apln.network/wp-content/uploads/2024/05/28331415919_18165c753d_o-scaled-e1715911457404.jpg)